Siapa, sih, yang masih suka baca teenlit sampai sekarang?
Ya aku. Ha-ha.
Padahal, sejak duduk di bangku SMP aku sudah akrab dengan genre ini. Anehnya, meski usia bertambah dan status berubah—bahkan sekarang sudah punya tiga anak—kecintaanku pada teenlit masih bertahan. Mungkin karena teenlit selalu punya cara sederhana tapi jujur untuk membahas luka, kehilangan, dan proses tumbuh yang sering kali kita anggap sepele.
Kali ini aku membaca 3600 Detik karya Charon. Novel ini mengisahkan seorang gadis bernama Sandra, yang tanpa ia sadari sedang berdiri di tengah keluarga yang perlahan retak. Selama ini Sandra merasa hidupnya baik-baik saja. Ia memang tidak terlalu dekat dengan ibunya yang sibuk sebagai wanita karier, tapi hal itu tak pernah menjadi masalah besar baginya. Kehadiran ayah yang hangat dan dekat sudah cukup untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam hidupnya. Bahkan ketidakhadiran ibunya di momen-momen penting pun tak pernah ia persoalkan.
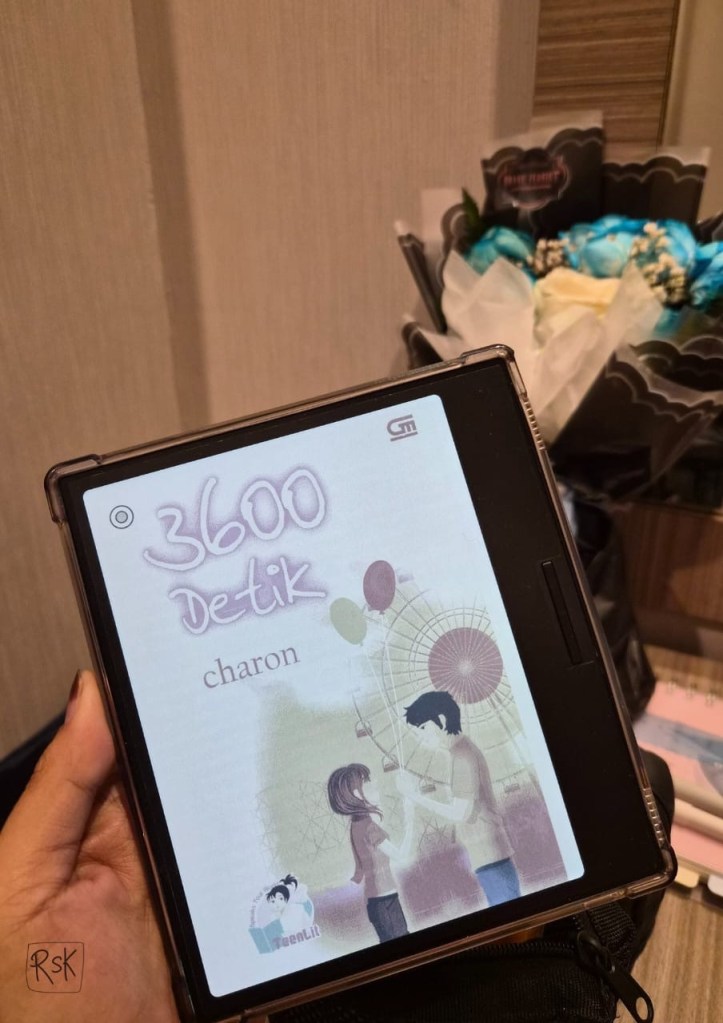
Sampai semuanya runtuh sekaligus.
Perceraian orang tuanya menjadi titik balik yang membuat dunia Sandra terbalik. Yang paling menyakitkan bukan hanya perpisahan itu sendiri, melainkan keputusan ayahnya untuk pindah ke luar negeri tanpa mengajaknya. Dari seorang anak yang merasa dicintai dan berharga, Sandra mendadak kehilangan pijakan. Ia merasa ditinggalkan, tidak dipilih, dan tak lagi penting.
Rasa kecewa itu menjelma menjadi amarah. Seperti banyak remaja yang terluka, Sandra melampiaskannya dengan cara yang salah. Ia mulai membuat keonaran di sekolah, merokok, membolos, dan menjadi sosok yang sama sekali berbeda dari Sandra yang dulu rajin dan tekun. Ibunya pun kelelahan—harus berulang kali memindahkan Sandra dari satu sekolah ke sekolah lain, mencoba memperbaiki keadaan yang terasa semakin sulit dikendalikan.
Hingga akhirnya, sang ibu mengambil keputusan besar: pindah kota. Harapannya sederhana, mungkin terlalu sederhana—lingkungan baru bisa menjadi awal yang baru pula bagi Sandra.
Namun kenyataannya, Sandra tidak berniat berubah. Ia justru bertekad tetap membuat masalah. Bukan tanpa alasan. Semua itu ia lakukan agar ibunya merasakan pusing yang sama, agar sang ibu menyerah, agar ia merasa diperhatikan. Sampai suatu hari, hidupnya bersinggungan dengan Leon—seseorang yang pelan-pelan mengubah arah cerita.
Sebagai bocoran kecil, 3600 Detik bukan tipe cerita dengan akhir bahagia yang manis. Tapi anehnya, akhir yang disuguhkan tidak membuatku kesal atau ingin menggerutu seperti novel sebelumnya yang pernah kubaca. Cerita ini terasa pahit, tapi jujur. Menyakitkan, tapi masuk akal. Seperti hidup itu sendiri.
Sebagai seorang ibu, membaca kisah Sandra membuatku berhenti sejenak. Aku jadi bertanya pada diri sendiri: apakah selama ini aku sudah cukup hadir, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional? Kadang kita merasa sudah melakukan yang terbaik—menyediakan kebutuhan, memastikan anak-anak aman dan terurus—namun lupa bahwa yang paling mereka butuhkan sering kali hanyalah merasa dipilih, didengarkan, dan dianggap penting.
3600 Detik mengingatkanku bahwa luka anak tidak selalu muncul dalam bentuk tangis atau kata-kata. Kadang ia menjelma menjadi amarah, kenakalan, atau sikap acuh yang melelahkan. Dan sebagai orang tua, mungkin tugas kita bukan langsung memperbaiki, melainkan bertahan untuk tetap hadir, bahkan ketika anak sedang berada di versi dirinya yang paling sulit dicintai.
Mungkin inilah alasan mengapa aku masih membaca teenlit sampai sekarang. Karena di balik kisah remaja, aku menemukan cermin—tentang anak-anak, tentang diri sendiri, dan tentang belajar mencintai dengan cara yang lebih sabar.
Pada akhirnya, 3600 Detik bukan hanya cerita tentang remaja yang terluka, tapi juga tentang keluarga yang sama-sama belajar memahami satu sama lain. Novel ini mungkin dibungkus dengan gaya teenlit yang ringan, namun menyimpan pesan yang dalam tentang kehilangan, kehadiran, dan kebutuhan untuk merasa dicintai tanpa syarat.
Sebagai ibu, buku ini meninggalkan satu pengingat penting bagiku: bahwa anak-anak tidak selalu membutuhkan orang tua yang sempurna, melainkan orang tua yang mau tinggal, mendengarkan, dan tidak pergi saat keadaan menjadi rumit. Karena sering kali, di balik sikap memberontak, ada hati kecil yang hanya ingin dipeluk dan diyakinkan bahwa ia tetap berarti.
Membaca 3600 Detik membuatku ingin lebih sering menepi sejenak, menurunkan ekspektasi, dan membuka ruang percakapan dengan anak-anakku—tentang perasaan, ketakutan, juga hal-hal kecil yang mungkin selama ini luput. Dan mungkin, itulah kekuatan cerita seperti ini: diam-diam mengajak kita pulang, tidak hanya sebagai pembaca, tetapi juga sebagai orang tua yang terus belajar.
Jika kamu mencari bacaan teenlit yang tidak sekadar manis, tetapi mampu meninggalkan rasa dan renungan, 3600 Detik layak diberi waktu—setidaknya 3600 detik untuk memahami bahwa tumbuh, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua, adalah proses yang tak pernah benar-benar selesai.
